
Maluku Utara dengan luas wilayah mencapai 140.255,32 km², sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya 33.278 km² (23,73%) adalah daratan. Daerah ini berada di jalur ring of fire atau cincin api dan menghadapi berbagai bencana. Ada kurang lebih 11 jenis bencana, salah satunya yang sering dirasakan warga adalah gempa bumi.
Seperti terjadi pada Jumat (15/11) dinihari tadi, gempa 7,4 magnitudo mengguncang sebagian Halmahera, Ternate, Tidore, Batang Dua higga ke Sulawesi Utara. Gempa yang berpotensi tsunami itu sempat membuat panik warga malam tadi. Sebagian warga bahkan tidak mau ambil risiko, memilih menjauhi pantai. Di Ternate meski tidak ada korban baik harta maupun jiwa, sempat menimbulkan kepanikan luar biasa, terutama warga di tepian pantai. Sementara daerah lain seperti di Pulau Batang Dua dikabarkan mengalami kerusakan fasilitas rumah warga.
 Kerusakan akibat gempa di Kelurahan Mayau, Batang Dua, Ternate. (foto:ist)
Kerusakan akibat gempa di Kelurahan Mayau, Batang Dua, Ternate. (foto:ist)
Data Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara menyebutkan, Maluku Utara memiliki beberapa ancaman serius bencana yakni gempa bumi, gunung api, abrasi oleh air laut, gelombang pasang, banjir bandang, banjir lahar dingin, longsor, puting beliung, kebakaran hutan, tsunami, banjir rob, kekeringan dan konflik horisontal. Semua bencana itu pernah terjadi di daerah ini. Sementara Ternate sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat Maluku Utara, juga menghadapi 11 jenis bencana ini. Tiga jenis bencana yang paling sering terjadi di pulau ini adalah, gempa bumi, gunung meletus dan banjir lahar dingin.
Dalam sebuah seminar bertema Melindungi Bumi dan Tangguh Menghadapi Bencana yang digelar Jurusan Geografi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate awal Mei lalu lalu ikut membicarakan persoalan ini. Tiga pembicara yakni Peneliti Senior Geofisika Univeristas Gadjah Mada, Dr Wiwit Suryanto, Ketua Forum Penanggulangan Bencana (PRB) Kota Ternate Abdul Kadir D Arief ST M.Eng dan Basri Kamarudin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Ternate, mengupas persoalan bencana dan mitigasi yang dihadapi warga daerah ini.
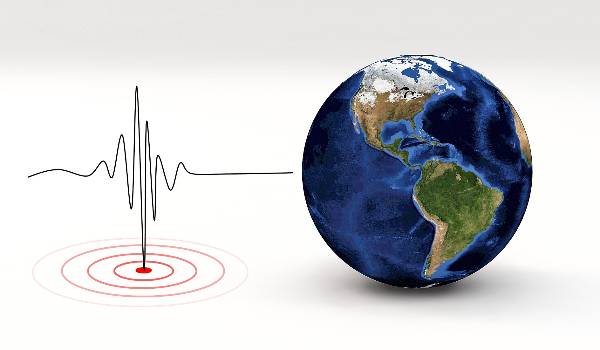 (Ilustrasi:pixabay)
(Ilustrasi:pixabay)
Wiwit misalnya, mengajak semua pihak belajar dari berbagai kejadian bencana di bumi ini. Dengan begitu bisa menjadi tangguh menghadapinya. Menurutnya, bumi ini jika masih aktif, menandakan masih ada kehidupan. Yang dikuatirkan malah jika bumi sudah tidak punya aktivitas lagi maka menjadi pertanda hidup bumi akan berakhir. “Penting kita belajar kepada bumi,” ujarnya.
Dia turut biacar soal trend bencana di Indonesia di mana sejak 2012 sampai saat trennya terus meningkat. Ini memberi isyarat negeri selain dianugerahi tanahnya yang subur, juga berada di kawasan yang rawan bencana. “Tsunami, gelombang pasang, tanah longsor, gempa bumi, banjir maupun gunung meletus ada di Negara kita. Karena ragam bencana itu Indonesia kadang diibaratkan sebagai 'Super Market Bencana'. Mau pilih bencana apa semua ada di Indonesia,” katanya.
 Tsunami Aceh. (Foto:pixabay)
Tsunami Aceh. (Foto:pixabay)
Trend bencana meningkat sejak 2012 sampai 2016. Ini bisa terjadi karena media informasi semakin maju sehingga informasi kejadian cepat ke mana-mana. “Kita harus belajar dari berbagai bencana itu agar bisa tangguh menghadapinya. Kenapa? karena kita hidup di daerah rawan bencana,” tuturnya.
Maluku Utara terutama Halmahera paling serius menghadapi bencana gempa bumi. Berdasarkan peta gempa seluruhnya tertutup kejadian gempa. Artinya seluruh Halmahera rawan bencana gempa bumi. “Secara statistik di Indonesia setiap sehari terjadi 17 kali gempa di atas 1 skala richter. Sementara yang bisa dirasakan terjadi 3 kali gempa setiap bulan. Jika diambil rata-rata, Indonesia merupakan Negara paling intensif dalam urusan gempa bumi. Hal ini membuat semua pihak memperhatikan fenomena gempa ini.
Selain gempa bumi, bencana lainnya adalah gunung api. Dua bencana ini ada di Maluku Utara terutama Halmahera dan sekitarnya. Selain gempa bumi juga dikelilingi gunung api. “Kalau pulau Jawa dilihat dari peta masih ada sela-sela artinya tidak didominasi gunung berapi. Halmahera dan pulau pulau kecil lainya dilihat dari peta dikelilingi gunung api.
Dalam catatan sejarah bencana alam di Maluku Utara terjadi sudah sejak lama. Khususnya gempa bumi dan gunung meletus. Berdasarkan catatan Belanda, November dan Desember 1550, di Galela, Halmahera Utara, Gunung Dukono meletus sangat besar. Bahkan menyebabkan air danau Galela naik sampai 4 meter atau terjadi tsunami air danau. Sementara di Ternate 1546 pada 29 September Ternate mengalami gempa sangat kuat. Sayang kejadian seperti ini sangat malas dicatat. Beruntung dicatat oleh Belanda sehingga bisa diketahui sejarah bencananya. Contoh paling nyata gempa di Jogjakarta. Sebenarnya sebelum gempa besar pada 2006, pada 1800 telah terjadi gempa yang sangat kuat. Hanya saja tidak tercatat. Akhirnya warga lupa dan merasa seperti tidak pernah terjadi musibah. Padahal dibuka sejarah, bencana besar itu pernah terjadi.
Untuk Ternate juga sama, wilayah ini dalam catatan sejarah memiliki kerawan bencana gunung api dan gempa bumi. Beberapa bukti seperti danau Tolire dan muculnnya batu angus adalah bukti dua bencana ini pernah terjadi di Ternate.
 Pemandangan Pulau Ternate. (Foto:pixabay)
Pemandangan Pulau Ternate. (Foto:pixabay)
Untuk bahaya yang mucul akibat bencana, dengan sains bisa dipelajari. Begitu juga kerentanan bisa dipelajari dan didesain. “Tugas kita yang mengenyam pendidikan mengetahui sumber bencana agar warganya diperkuat. Dengan begitu, minimal bisa tanggap terhadap kejadian bencana. Satu poin paling penting, education atau training, yakni memberi pendidikan terkait bencana gempa maupun gunung meletus kepada warga."
Dia contohkan di Jepang, mitigasi bencana didapatkan siswa mulai dari SD. Karena itu ketika terjadi gempa mereka sudah tahu cara berlindung dan menyelamatkan diri. Daerah kita juga butuh mitigasi secara kontinyu. Dia membandingkan mereka yang paham mitigasi, di Jepang misalnya, pernah terjadi gempa yang kekuatanya sama dengan kejadian Jogja 2006, tetapi korbannya hanya satu orang. Itu juga bukan korban langsung gempa, tetapi penyakit jantung. Sementara di Jogjakarta dengan kekuatan yang sama korban meninggal sampai 6 ribu orang. Di sinilah perbandingan perbedaan kapasitas warga soal mitigasi bencana.
Di Indonesia memperkuat kapasitas masyarakat agar tangguh bencana, masih menjadi masalah, terutama dalam hal training. Padahal dengan training mereka bisa mengetahui di mana lokasi bahaya, berapa besar bahayanya dan lain-lain.
Dalam manajemen bahaya, ada beberapa tahapan harus dilalui. Sayangnya kadang lebih senang di tahap penyelesaian atau post disasater. Lebih asyik di tingkat ini karena upaya mitigasi itu kadang hasilnya belum bisa dilihat secara langsung.
Baginya, gerakan mitigasi melalui sains itu sangat penting, sayang, kadang tidak seseuai harapan. Dalam hal riset saja susah dibiayai. Padahal, ini sesuatu yang penting. “Mitigasi bencana itu juga butuh riset,” ucapnya. Daerah rawan bencana jika tidak dialokasikan sumberdaya anggaran riset, dipastikan dampaknya anggaran untuk post disaster akan lebih besar. “Alokasi biaya respon bencana dan biaya riset mitigasi bencana pasti jomplang,” katanya.
 Ilustrasi kerusakan akibat gempa. (foto:pixabay)
Ilustrasi kerusakan akibat gempa. (foto:pixabay)
Selain penganggaran riset yang minim, management data juga bermasalah. Ini menjadi tantangan dan perlu dipikirkan bersama. Soal data bagi peneliti itu sangat penting. Meskipun seiring waktu soal data ini semakin baik. Ini setelah banyak data pemantauan gunung api, gempa dan lain-lain sudah disediakan instansi terkait.
Yang bermasalah lagi yakni resources sharing. Kadang-kadang periset membutuhkan data, dibuat berbelit-belit. Proses mendapatkannya susah, prosedurnya panjang dan rumit. Diharapkan ke depan lembaga pemerintah dan lembaga penelitian di kampus harus ada sinergi dan kerjasama.
Soal saintis lainnya adalah dalam memprediksi bencana masih sulit. Sampai sekarang para ahli, berusaha bisa memahami proses bencana itu terjadi, baik gempa bumi maupun gunung meletus. Pemahaman proses kejadian bencana sampai saat ini belum bisa dikuasai. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Para saintis berpacu untuk belajar. Diharapkan suatu saat mereka sudah bisa memprediksi kapan gempa atau gunung meletus terjadi.
Terakhir, persoalan yang dihadapi adalah mengkomunikasikan bencana kepada masyarakat. Hal ini masih menjadi kendala. Dalam berbagai kejadian ada gap antara sains dan bahasa awam. Satu hal yang terkait dalam sains yakni ketidakpastian, error dan uncertainty. Sementara masyarakat ketika dijelaskan dan ada error, pasti susah diterima. Ini tantangan menjelaskan soal bencana kepada masyarakat. Apalagi proses bencana yang belum diketahui, bisa jadi keliru atau tidak sesuai harapan.
Dalam hal mitigasi peran kampus juga sangat dibutuhkan untuk peningkatan SDM. Tujuannya bisa memberi kontribusi kepada masyarakat memahami dan melakukan mitigasi. Baik secara individu maupun secara massal. Peran ini tidak hanya universitas atau lembaga riset tetapi menjadi satu kesatuan dengan masyarakat dan pemerintah. Sebab apapun hasil riset itu jika tidak didukung kebijakan pemerintah akan menjadi sia-sia.
Ternate Paling Rawan Gempa dan Gunung Api Gamalama
Soal Penanggulangan Resiko Bencana (PRB), Kota Ternate sebagai sebuah kota kecil, memiliki gunung api menghadapi juga gempa bumi dan bencana lainnya. Menurut Ketua PRB Ternate, Abdul Kadir Arief, dilihat dari berkembangnya pembangunan kota, yang mengarah pada ancaman bencana yakni pembangunan menuju ke arah gunung api. Begitu juga reklamasi pantai yang sudah hamper mengelilingi pulau Ternate. Sesuai peta perkembangan penggunaan lahan, telah terjadi perubahan landscape pantai maupun daerah perbukitan Pulau Ternate.
Kota Ternate menghadapi bahaya bencana gunung api, banjir bandang, lahar dingin, gelombang pasang, banjir rob, gempa bumi, abrasi dan tsunami. Yang harus menjadi perhatian serius adalah trend gunung berapi Gamalama yang berubah di 2018 ini. Di mana aktivitasnya tidak lagi dipengaruhi aktivitas tektonik sebelumnya.
 Pemandangan Pulau Ternate dan Tidore.(foto:pixabay)
Pemandangan Pulau Ternate dan Tidore.(foto:pixabay)
Laporan Pemantau Gunung Gamalama Oktober 2018, menjelaskan letusan gunung dipicu oleh gempa tektonik. Gempa ini ikut memicu efulsif di gunung Gamalama. Ini menunjukan ada satu trend yang berubah. Ini mesti menjadi ikhtiar bersama.
Gamalama dulunya tidak dipengauhi gempa tektonik, kini bisa dipengaruhi gempa di Halamhera dan daerah lainnya. Jika terjadi gempa di luar Ternate pun ikut memicu aktivitas Gamalama yang signifikan. Perkembangan bencana gunung api yang berubah, sementara di sisi pembangunan pemukiman warga, semakin menuju ke daerah puncak. Begitu pun pemerintah daerah semakin mengembangkan reklamasi mengelilingi semua kawasan pantai di Ternate.
 Ilustrasi letusan gunung. (foto:pixabay)
Ilustrasi letusan gunung. (foto:pixabay)
Pada 2001 pengembangan kota ini masih biasa. Pantai belum direklamasi dan elevasi Gamalama belum disentuh pembangunan pemukiman. Setelah 2019 semuanya berubah. Pembangunan merambah ke daerah puncak dan reklamasi massive terjadi. Proses pembangunan yang menyerang pantai dengan reklamasi dan membangun ke daerah elevasi lebih berbahaya dari aktivitas Gamalama.
Ini menunjukan proses pembangunan tanpa melalui kajian mendalam melibatkan akdemisi dan pakar. “Kota ini kadang dibangun tanpa kajian detail. Terkesan hanya proyek untuk mengejar pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan dampak bencana yang akan terjadi,” katanya. Wajah pantai Ternate misalnya berubah. Ini menunjukan proses tata guna lahan yang berubah dan dipaksakan manusia. Sebuah contoh di kawasan Dodoku Ali sebuah teluk yang dulunya menjadi tempat berlabuh kapal dan lain-lain, kini menjadi daratan buatan dengan berbagai pembangunan fisik. Kondisi ini sebenarnya menjadi trigger bencana yang ditopang oleh manusia.
Ternate hari ini dan ke depan menghadapi 11 jenis bencana yang sangat mengancam. Ketika pembangunan merambah kawasan puncak, persoalan yang dihadapi adalah ancaman gunung api. Sementara pemerintah kesulitan melarang warga membangun menuju arah puncak atau Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.
Dalam kasus ini, yang jadi soal adalah semangat konservasinya. Pembangunan mengarah daerah puncak diperbolehkan tetapi perlu ada ketentuan yang diatur pemerintah. Ternate membutuhkan model pengembangan kota yang memikirkan dampak besar gunung api Gamalama. Begitu juga pengembangan kota mengarah ke pantai. Apakah kota ini harus berdiri di atas kawasan reklamasi?.
Di tengah kepadatan penduduk luar biasa dan ancaman bencana gunung api perlu segera dicari solusinya. “KIta semua berharap tidak terjadi bencana, tetapi dengan kondisi sekarang jika terjadi bisa jatuh korban cukup banyak,” katanya. Karena perlu ada upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan pengembagan kapasitas masyarakat, termasuk di lingkungan akademik. Membangun kesadaran itu dari lingkungan akademik terlebih dahulu. Mustahil membangun di tingkat masyarakat tetapi tingkat akademisnya belum ada kesadaran.
 Ilustrasi kerusakan akibat gempa. (foto:pixabay)
Ilustrasi kerusakan akibat gempa. (foto:pixabay)
Diharapkan, perguruan tinggi di Ternate bersama sama memiliki kepedulian mengurangi tingkat resiko bencana. Selain itu butuh penyediaan infrastruktur mengatasi bencana alam. Upaya ini mungkin sudah mulai dilakukan dengan dibuat jalur evakuasi bencana gunung api. Ke depan perlu membangun shelter untuk tsunami. Dengan perkembangan tata ruang Ternate shelter itu bisa dibangun dan dirawat.
Butuh juga payung hukum untuk penanggulangan bencana dan PRB . Perda Kota Ternate 2014 Tentang Penanggulangan Bencana menjadi payung hukum., Diharapkan menjadi dasar bagi pembangunan Kota Ternate yang lebih memikirkan dampak bencana. (*)
Catatan: Artikel ini pernah dimuat di Mongabay.co.id
Ditulis Oleh : Mahmud Ichi
Pada Tanggal : 15/11/2019