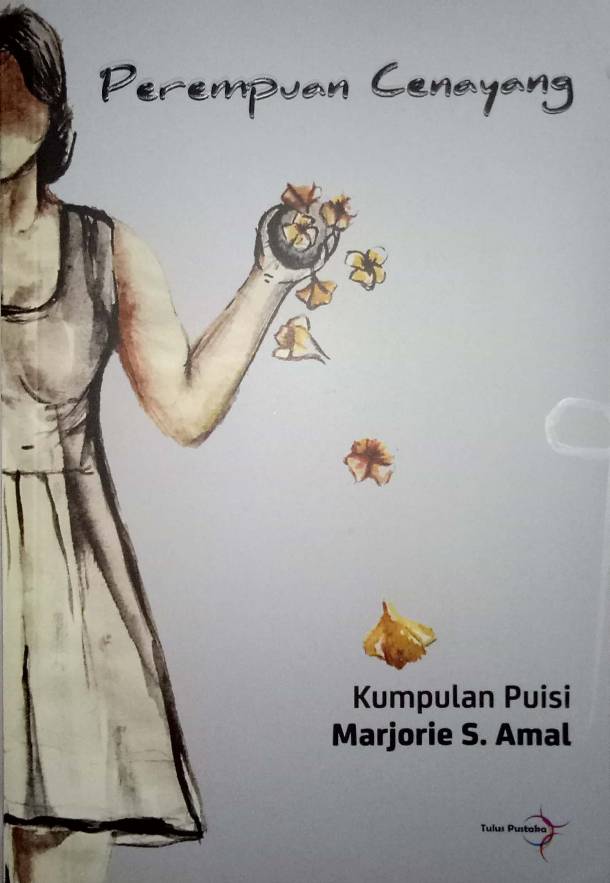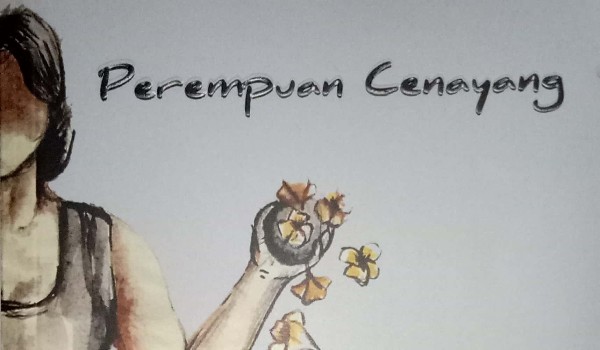
"Setiap tulisan, setiap teks, pada akhirnya harus bertahan pada kekuatannya sendiri dengan mengandalkan otonomi semantiknya sendiri, setelah dia dibebaskan dari ketergantungan pada penulis dan pengarangnya." (Ignas Kleden, 2004:208)
(I)
Pertama-tama, ijinkan saya mengajukan diri, bahwa saya, sebenarnya tidak memiliki perkakas keilmuan yang cukup dan otoritatif di bidang sastra untuk membahas secara detil apa yang tersirat dan tersurat dalam buku antologi puisi, "Perempuan Cenayang" karya Marjorie S. Amal (2019) yang, terus terang, sarat makna. Saya akan "membaca" secara awam dari sisi yang lain. Menafsir dengan cara yang –mungkin-- biasa saja atau boleh saja keliru, sesuai perkakas dan pemahaman yang saya miliki. Bagaimana pun, setiap teks yang telah dilahirkan dari "rahim" setiap pengarang/penulis, maka segala tafsirannya akan menjadi milik siapa saja.
(II)
"Perempuan Cenayang" merupakan judul dari antologi puisi pertama (?) Marjorie (selanjutnya akan digunakan pengarang). Bila dicermati lebih jauh, memang bukan soal "perempuan" yang "dikata-katai" pengarang, ada banyak hal yang diimajinasikan. Antologi ini terbagi dalam empat bagian besar sebagai "tema": Perempuan/Cinta/Tempat/Waktu. Sebagian besar, berisi pergumulan dan pergulatan batin pengarang dengan realitas yang dihadapinya, dan juga apa yang dihadapi sebagian besar orang Maluku Utara. Sekalipun begitu, pengarang dengan "lincah dan cerdas" menyembunyikan apa yang dialami melalui bahasa simbol. Bahkan kerap "menitipkan" diksi penuh nuansa lokal: pala/fuli/Halmahera/Galela/Tanjung Bongo/Petani Kopra.
Perhatikan bait-bait puisi berikut:
Sang Perempuan
adalah kita perempuan
yang menggempitakan panen ketika pala meranum
mentasbihkan puja ketika fuli memerah
menistakan penat ketika tanah subuh terjejakadalah kita perempuan
yang bersua para lelaki yang melaut
kadung mencintai para lelaki di pedalaman dan pesisir
puas menelanjangi setiap lekuk Halmahera
semata untuk menggerus keterasinganadalah kita perempuan
tak menyuarakan sinisme ketika peran dikerdilkan
tak melantunkan perih ketika lelaki kami hilang saat perang
tak lantas menggaungkan sarkasme
ketika harta bumi diterbangkan
melenyapadalah kita perempuan
hanya meneriakkan hening agar dimengerti
tanah ini dititipkan untuk kami juga
di pangkuan para perempuan Halmahera (1)
Pada bait-bait puisi di atas, pengarang hendak meletakkan bagaimana "posisi" dan eksistensi perempuan Halmahera yang tegar, jauh dari sifat cengeng, walau perang telah merenggut seluruh harapannya. Dalam tafsir ini, kemungkinan perang itu adalah "konflik kekerasan" yang pernah melanda Halmahera dan Maluku Utara. Di sini, pengarang dengan menggunakan frasa perempuan, berhasil mendeskripsikan konflik dengan begitu "lembut" dan flawless.
Dalam tafsiran Michel Foucault (2) terdapat hubungan timbal balik antara pengetahuan (savoir) dengan kekuasaan (pouvoir). Di mana kekuasaan terartikulasi ke dalam pengetahuan, dan sebaliknya pengetahuan terartikulasi ke dalam kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya memiliki "relasi" dengan pengetahuan, melainkan kekuasaan terdiri dari pengetahuan, sebagaimana pengetahuan juga terdiri atas kekuasaan. Yang ingin disampaikan, dengan meminjam tafsiran Foucault di atas, melalui bahasa sastra (puisi) pada bait-bait di atas, pengarang tengah memperlihatkan "kekuasaannya" untuk mengutuk praktik-praktik kekerasan yang merampas apa yang dimiliki kaum perempuan.
Bandingkan bait puisi berikut:
Namaku Rabiyah
aku pekerja pemimpi
pagi hingga malam buruh pabrik
tengah malam memilin rahasia
akhir pekan bertualang menjadi racun
"kau boleh bekerja di sini, tapi singkapkan rokmu kapanpun kumau, dirimu."
lelaki itu berbisik serupa godam
retakkan harga diriku
seolah di pasar lelang......
namaku Rabiyah
gajiku serdadu kerjaku panglima
kemanusiaan entah berpihak pada siapa (3)
Di tangan dan imajinasi pengarang, sosok perempuan begitu berwarna dan bergolak. Pengarang benar-benar "berkuasa" melontarkan bahasa dan simbol dengan cara yang tak disangka. Tetapi, bait puisi berikut ini memberi penegasan berbeda:
Pinanglah Aku
kekasih, pinanglah aku
cukup bawakan satu piring antik dan kain putih segulung
karena aku perempuan Galela
namun jangan kau kira aku perempuan sederhana
kusulam harapan bukan di atas kain putih itu
tapi di tepian bintang tertinggi, di mega galaksi terjauh
kuingin anak kita tak dibesarkan kuasa alam semata
tapi oleh tanggungjawab dan didikan hebat kitajangan pula mengira aku perempuan putus asa
kulukis mimpi bukan di balik piring antik itu
tapi di lengkung pelangi, di dekapan angin pulauku
kuingin anak kita tak mendewakan akal dan nalar semata
tapi juga cinta kasih, intuisi, tradisi, dan etika moralkekasih, pinanglah aku
bawakan juga rembulan dan matahari dalam kotak sirih
pinang
agar mereka tak saling merajuk
hingga kita tak perlu lagi mendefinisikan cinta (4)
Pengarang tidak larut dalam keindahan kata dan kalimat yang dikonstruksinya. Kekuatan makna yang merunjang seolah ikut menyeret dan membawa alam pikiran kesadaran pembaca. Dalam kelenturan kata dan diksi yang menyelinap sangat dinamis dalam untaian rangkaian kalimat yang ada, diam-diam pengarang menyisipkan pesan-pesan moral, nilai, makna filosofi, dan ungkapan lokal. Pada puisi "Aku Tak Suka Bunga dan Ranjangmu" (hlm. 51), "Geliat Tanjung Bongo" (hlm. 61), "Di Dapur" (hlm. 71) dan “Saat Berbuka Puasa” (hlm. 90), terasa gurih persoalan yang dilukiskan. Perempuan masih menjadi fokus bagi sang pengarang. Pada puisi "Petani Kopra" (hlm. 64) pengarang juga mampu menunjukkan eksistensi, identitas, dan "kemarahannya" manakala kopra tak lagi berharga di mata petani.
Rudolf Unger yang dikutip Endraswara (5) mengklasifikasikan permasalahan yang digarap seorang pengarang, sebagai berikut: pertama, masalah nasib, yakni hubungan antara kebebasan dan keterpaksaan, semangat manusia dan alam; kedua, masalah keagamaan, termasuk interpretasi tentang Yang Kudus, yang suci; ketiga, masalah alam, perasaan terhadap alam juga mitos dan alam gaib; keempat, masalah manusia, ini menyangkut manusia, hubungan manusia dengan kematian dan konsep cinta; kelima, masalah masyarakat keluarga, dan negara.
Tentang Yang Kudus, yang suci, pengarang merangkum dalam setangkup puisi “Saat Berbuka Puasa”.
Saat Berbuka Puasa
kujerang pucuk the pada tungku abu-abu
meramu bening santan dengan alif ba ta
pandan seikat hijaukan dasar panic
merebus gelora panas perihal kepulanganmu
hingga aroma manis jatuh dari peluhku
diburu suara adzanmari duduk berhadapan, kekasih
aneka takjil hiasi meja
retakkan puasa
di punggung langit doa untuk-Nya
aksara menebar syukur
maka Bismillah (6)
Karena itu, dalam sosiologi sastra, hakikat karya sastra sebagai sebuah rekaan, memerlukan pemahaman lain yang berkaitan dengan kesadaran pengarang dalam memperlakukan fakta-fakta sosial (7). Pengarang "berhasil" memanfaatkan kemerdekaannya dengan membangun metafor-metafor dan menyimpan rapi dalam struktur imajinasi bahasa tentang realitas yang sesungguhnya. Tentang bagaimana: perempuan, cinta, tempat, dan waktu diperlakukan.
(III)
"Perempuan Cenayang" hampir pasti, merangkum lima unsur dari Unger di atas. Dan, oleh pengarang, keempat tema besar antologi ini sangat cair dan lincah bolak-balik dalam membangun otonomi semantik. Membiarkan pembaca berkelana di rimba kata, diksi, frasa, dan kalimat yang dipakai sembari mencari makna-makna tersembunyi.
Menurut Ignas Kleden (8), otonomi semantik membebaskan sebuah teks dari tiga ikatan. Pertama, teks dibebaskan dari ikatannya dengan pengarang. Di sini, teks bebas ditafsirkan oleh siapa saja, tidak terikat dengan maksud pengarang; Kedua, sebuah teks juga dibebaskan dari konteks di mana semula dia diproduksikan. Teks yang ditulis sebagai kenang-kenangan pribadi dapat dijadikan sebagai sumber sejarah; Ketiga, sebuah teks dibebaskan dari hubungan yang tadinya terdapat di antara teks itu dan kelompok sasaran kepada siapa teks itu semula ditujukan. Otonomi semantik selalu memungkinkan bahwa sebuah teks didekontekstualisasikan, dan kemudian direkontekstualisasikan kembali.
(IV)
Lokus pada perempuan merupakan kenyataan hidup sehari-hari "di sini dan sekarang", sebuah realissimum (yang paling nyata) bagi sebuah kesadaran (9), yang sengaja dihadirkan pengarang untuk menguatkan "kekuasaan" melalui bahasa sastra, sekaligus "menggedor" kesadaran pembaca, tentang pentingnya perempuan dalam segala lini kehidupan.
Lalu, pada puisi "Usai" (hlm. 11), dan "Usai" (hlm. 95), dua judul yang sama, namun memiliki pendalaman makna yang sulit untuk diterka. Apakah ini sebuah polisemi? Atukah memang dimaksudkan demikian. Saya tak bisa memberi tafsir soal ini.
Bagi saya, "Perempuan Cenayang" telah memberi wajah baru bagi sastra tanah air. Setidaknya, beberapa kata, diksi, dan frasa lokal telah diseret ke tengah-tengah perbincangan sastra, yang mungkin saja selama ini, kurang diketahui. Antologi puisi “Perempuan Cenayang” telah ikut menambah dan menyemarakkan khazanah sastra Maluku Utara. []
Catatan Kaki
(1) Marjorie S. Amal, Perempuan Cenayang, Kumpulan Puisi, Cimahi Tengah : Tulus Pustaka, 2019, hlm. 12
(2) Michel Foucault, Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writing 1972-1977. New York : Pantheon Books, 1980, hlm. 98
(3) Marjorie S. Amal, Op.Cit. hlm. 14
(4) Marjorie S. Amal, Ibid, hlm. 41
(5) Lihat, Suwardi Endraswara, Filsafat Sastra, Hakikat, Metodologi, dan Teori, Yogyakarta : Layar Kata, 2012, hlm. 62-63
(6) Marjorie S. Amal, Op.Cit, hlm. 90
(7) Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 97
(8) Ignas Kleden, Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan, Esai-Esai Sastra dan Budaya, Jakarta : diterbitkan atas kerjasama PT Pustaka Utama Grafiti dan Freedom Institute, 2004, hlm. 107
(9) Peter L. Berger, and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality; A Treatise in the Sociology of Knowledge. London : Penguin Books, 1966, hlm. 36